Pertengkaran
yang terjadi antara aku dan kakakku sore ini berakhir dengan pelukan maaf. Mbak Tara berjanji untuk tetap menjagaku
dan mencoba mengubah penyampaian pesannya agar tak menyinggung perasaanku dan
aku berjanji untuk dapat lebih menerima apa yang kakakku pesankan demi
kebaikanku sendiri. Tapi pertengkaran itu tak hanya membuat aku dan kakakku
lebih memahami satu sama lain. Apa yang terjadi sore ini sedikitnya membuatku
takut pada kakakku. Tidak, ia tak sampai melakukan kekerasan fisik padaku.
Hanya saja saat kakakku tiba-tiba diam dan nampak begitu serius, dengan mata
yang hampir tak berkedip dan menatap kaku apa yang ada di depannya, aku harus
memahami bahwa ia mengetahui sesuatu; sesuatu yang mungkin bagusnya tak
kuketahui.
Dan mbak Tara pun mengancam Ferry untuk tak
mendekatiku lagi. Ia melakukan itu di hadapan banyak orang, teman-temanku dan
juga aku sendiri. Mbak Tara bahkan
hampir menampar Ferry, jika saja Ezra tak segera bertindak untuk menahan
kakakku. Mbak Tara begitu saja
membawaku keluar dari restoran itu dan menyuruhku untuk masuk ke dalam mobil.
Karena kejadian itu, aku terpaksa membatalkan rencanaku untuk pergi bersama
kakakku dan Ezra ke sebuah tempat karaoke dan bertemu dengan Reyhan, Evan dan
Riani disana. Rencanaku sore ini adalah mengobrol dengan teman-temanku lalu
bersama-sama bersenang-senang bernyanyi dan menikmati lagu-lagu. Namun rencana
itu tak terrealisasi dan semua itu karena kakakku.
“Kamu nggak lihat dia mau apa tadi?!” tegas mbak Tara.
“Emang dia
mau apa? Apa yang mbak lihat dari dia?” tanyaku ketus.
“Tania! Dia
itu udah rangkul-rangkul kamu! Kamu
malah diem aja dan malah asyik ngobrol!” jawab mbak Tara.
“Ya udah sih, mbak! Cuma dirangkul ini!” balasku kesal.
“Cuma
dirangkul kata kamu? Kamu nggak lihat
tatapan dia kayak gimana?!”
Aku
meringis pelan. Kulirik kakakku yang sedang mengemudi dan menatap lurus jalanan
yang ada di depannya.
“Emang dia natap aku kayak gimana? Emang mbak tahu Ferry orangnya kayak gimana? Mbak nggak kenal dia, ‘kan? Mbak
baru kenal hari ini, ‘kan? Jadi mbak
jangan pernah ikut campur lagi urusan persahabatan aku!” tegasku.
Kami mulai
memasuki jembatan flyover dan kakakku
menancap gas lebih dalam, mempercepat laju mobil ini untuk bersaing dengan
kendaraan lain. Hujan deras menerpa kaca depan mobil dan menciptakan bunyi
ribut bersahutan seperti serangkaian bunyi tembakan senjata. Wiper bergerak cepat, mengenyahkan
titik-titik air yang mencoba menembus tebalnya tempered glass yang melindungi kami dari serangan tersebut.
“Kamu duduk
di sebelah dia dan kamu fokus ngobrol
sama Ezra yang ada di depan kamu! Mana bisa kamu lihat mata dia!” jawab mbak Tara.
“Aku sempat
lihat dia tapi dia biasa aja!”
tukasku, “Mbak Tara berlebihan tau nggak?!”
“Mbak bukannya berlebihan! Kamu mau dia
seenaknya rangkul kamu terus lama-lama bisa bertingkah lebih daripada itu?!”
sanggah mbak Tara.
Kami
melewati tiang pancang jembatan flyover
dan kakakku semakin mempercepat laju mobil. Hujan nampak semakin deras dan
sejujurnya aku mulai merasa takut. Jarak pandang perlahan berkurang dan
pecahnya titik-titik air di permukaan kaca depan tentu saja menghambat
pandangan kakakku yang sedang mengemudi. Belum lagi jalanan yang licin dapat
membahayakan kami. Aku takut jika kakakku melakukan sebuah kesalahan—bahkan
kesalahan kecil sekalipun—yang dapat membunuh kami berdua. Mbak Tara menekan klakson beberapa kali, mengusir
kendaraan-kendaraan yang ada di depannya agar mau ingkah dari jalannya. Ia
menyalakan lampu kabut dan meskipun demikian, tetap saja jarak pandang dari
tempat dudukku tak bertambah.
“Memang
Ferry mau ngapain? Itu tempat umum, mbak! Ferry nggak akan mungkin lakukan hal-hal aneh di tempat umum!” bantahku.
“Oh, jadi
kalau bukan di tempat umum kamu bisa ngebiarin
Ferry ngerangkul kamu, bahkan
melakukan hal yang lebih daripada itu?!” tanya kakakku sinis.
“Mbak Tara coba bilang kalau aku gampangan?!” aku semakin geram.
“Terus mbak harus bilang apa lagi?” jawab
kakakku dingin.
“Tania udah bilang kalau mbak nggak tahu apa-apa tentang Ferry, mbak jangan sembarangan nilai dia! Dan
juga, jangan pernah mbak anggap aku gampangan karena aku nggak kayak gitu!” bentakku.
“Kalau
memang kamu nggak gampangan, jangan
mau lagi dideketin sama cowok kayak Ferry!” mbak Tara balas membentakku.
Aku
terpukul. Tangisku meledak saat mobil mulai mendekati akhir jembatan. Aku tak
ingin melihat kakakku. Kupalingkan pandanganku ke luar jendela dan dengan mata
yang berkaca-kaca, dapat kulihat langit hitam menyelimuti areal pemakaman yang
seolah menyambut kami saat kami turun dari jembatan flyover tersebut. Kakakku menaikkan volume suara radio dan suara
bas yang keluar semakin berdebum. Kukecilkan volume suara radio dan kakakku
kembali menaikkannya. Kesal, kumatikan radio mobil dan akhirnya tak ada suara
apapun yang terdengar kecuali isak tangisku.
“Kenapa mbak Tara nggak bisa paham perasaan orang lain? Kenapa mbak Tara selalu blak-blakan kalau bicara dan nggak mikirin apakah
orang lain sakit hati atau nggak?
Kenapa mbak Tara berani perlakukan
Ferry di depan umum kayak gitu dan bikin aku malu di depan teman-teman aku? Apa salah aku, mbak? Coba jawab!”
Dan kakakku
tak bergeming.
“Tuh lihat sekarang! Mbak Tara malah
diam aja! Kenapa sih kalau mbak salah, mbak nggak mau mengaku kalau memang mbak salah? Mbak ini pengecut atau bukan!”
Kakakku
masih tetap tak bergeming. Ia tetap berfokus pada kemudi yang dipegangnya.
Jalanan mulai padat dan laju kendaraan kami pun tersendat karena kemacetan yang
ada di hadapan kami. Aku mulai kewalahan dengan tangisku sendiri. Beberapa
lembar tisu kuambil untuk menyeka air mataku.
“Selama ini
aku nggak pernah ikut campur dalam
urusan mbak Tara. Aku nggak larang waktu mbak Tara bilang mbak
mulai dekat sama mas Dika, ‘kan? Aku
juga nggak pernah larang mas Dika buat datang ke rumah”
Mobil terus
melaju perlahan dan aku masih tetap menangis. Aku ingin cepat-cepat turun dari mobilku
lalu mengunci diri di kamarku. Aku tak ingin diganggu oleh siapapun, terutama
oleh kakakku. Bahkan jika saat ini sedang tak hujan, aku bisa saja nekat
membuka pintu mobil dan berlari pulang karena kompleks perumahan tempat kami
tinggal berada tak jauh dari tempat kami terjebak saat ini. Lampu sein kiri
menyala dan kami berbelok, akhirnya memasuki jalanan dengan lalu lintas yang
tak padat. Di samping kanan berdiri sebuah pusat perbelanjaan yang menyatu
dengan sebuah hotel yang baru berdiri. Kami pun kembali berbelok ke kiri, melewati
gerbang kompleks perumahan, lurus melaju sejauh beberapa meter lalu kembali
berbelok ke kanan dan pada akhirnya tiba di depan rumah. Tanpa pikir panjang
aku membuka kunci pintuku dan keluar dari mobil. Kubuka pintu pagar dan, tidak menghiraukan kakakku yang memanggilku, mengetuk pintu rumah dengan
tergesa-gesa. Pintu rumah terbuka dan aku segera masuk, tak peduli dengan ayah
yang bertanya apa yang terjadi. Kukunci diriku di dalam kamar dan kembali aku
menangis. Mengapa mbak Tara begitu
jahat padaku?
Dan saat
mataku terbuka kusadari hujan telah berhenti. Jam dinding menunjukkan pukul
tujuh malam. Aku pasti tertidur saat menangis tadi. Kuperiksa ponselku dan
kulihat beberapa panggilan tak terjawab yang masuk, salah satunya adalah Ezra.
Aku segera menghubunginya kembali dan tak berapa lama suara Ezra pun terdengar.
“Kamu udah sampai rumah?” tanya Ezra.
“Udah. Aku minta maaf ya karena hari ini nggak bisa ikut karaoke,” jawabku.
“Nggak apa-apa. Sekarang aku lagi sama
Evan dan Reyhan di CiWalk. Biasa nih,
ngasuh si Reyhan main di Game Master
sambil nunggu dia dijemput abangnya,”
ujar Ezra.
Terdengar
samar-samar musik yang biasa kudengar saat Reyhan bermain permainan musik dan
tari dengan panel lima arah. Anak itu pasti sedang bersenang-senang saat ini.
“Biasanya
Reyhan main sama Andra dan Gea. Kemana memang mereka?” tanyaku.
“Andra sama
Gea nggak bisa ikut. Dilla lagi di
toko buku. Riani sendiri akhirnya nggak
bisa ikut karena mendadak harus ngasih
les tari ke anak-anak di komplek rumahnya,” jawab Ezra.
“Jadi
akhirnya hanya kalian cowok bertiga
yang pergi?” tanyaku.
“Ya. Habis
ini kayaknya mau langsung makan,”
jawab Ezra, “Oh ya, kita juga ketemu
Ferry kok tadi di tempat parkir”
Aku
terkejut.
“Ferry?”
“Ya. Ferry.
Dia sama Asha tadi aku lihat. Mesra banget
mereka sambil rangkul-rangkulan”
“Rangkulan?”
“Ya. Tapi nggak tau kenapa tadi pas kita papasan
sama mereka, Reyhan dan Evan bilang kalau mereka nggak suka lihat Ferry. Kata Evan sih cara Ferry ngeliat
Asha itu beda. Kalau Reyhan sendiri bilang tatapan Ferry itu mesum”
Aku menelan
ludahku. Apa mungkin yang kakakku katakan tentang Ferry itu benar?
“Mesum?”
“Kata
Reyhan sih gitu. Evan juga bilang gitu sih akhirnya. Tan, saran aku sih kamu jangan terlalu dekat sama
Ferry. Takutnya dia ada niat buruk”
Ucapan Ezra
terngiang-ngiang di benakku dan samar-samar aku masih dapat mendengar apa yang
kakakku katakan tentang Ferry. Saat aku mengingat kembali apa yang Ferry
lakukan saat kami berada di restoran sore ini, aku merasa menyesal. Mengapa aku
membiarkannya merangkulku? Mengapa aku tak memperhatikan caranya menatapku?
Mengapa aku begitu ceroboh? Seandainya mbak
Tara tak membentak Ferry dan menyuruhnya untuk tak merangkulku, mungkin Ferry
bisa saja melakukan hal yang lebih jauh. Seandainya mbak Tara tak duduk berhadapan denganku, pasti tak akan ada yang
menyadari tatapan Ferry padaku. Dan seandainya aku tak mengajak mbak Tara untuk pergi denganku, tak akan
ada yang menyelamatkanku saat Ferry mulai bertingkah terlalu jauh. Kurasa ini
semua mulai masuk akal. Pantas saja Ferry sempat bertanya padaku apakah aku
suka minum cocktail dan ia sempat
menawariku bir yang ia minum.
Kutaruh
ponselku di atas mejaku lalu perlahan berjalan keluar kamar. Tepat di depan
pintu kamar kakakku aku terdiam sejenak. Aku menyesal telah membentaknya,
memarahinya dan menyalahkannya. Seharusnya aku sadar bahwa kakakku mencoba
untuk menyelematkanku dan ia sedang melindungiku. Kuketuk pelan pintu kamar
kakakku dan akhirnya pintu itu terbuka. Mbak
Tara melepas headset yang ia kenakan.
“Ada apa?”
tanyanya.
“Aku minta
maaf. Yang mbak bilang tentang Ferry
itu bener,” ujarku pelan.
“Mbak juga minta maaf, Tan. Harusnya cara
mbak kasih tahu kamu nggak seperti itu. Mbak harus ubah cara penyampaian mbak,” jawabnya.
Mbak Tara lalu
memelukku dan mengusap pelan rambutku.
“Ezra
bilang tadi dia lihat Ferry sama Asha. Kata Ezra, Evan sama Reyhan nggak suka dengan Ferry karena cara Ferry
natap Asha itu beda,” jelasku.
“Dari awal mbak perhatiin
Ferry, mbak langsung mikir ada yang nggak beres sama orang itu. Taunya
betul, ‘kan?” balas kakakku.
“Ya. Aku
minta maaf. Harusnya aku mau dengar apa kata mbak”
Mbak Tara melepaskan pelukannya.
“Ya sudah.
Sekarang mbak mau lanjut revisi lagi. Kamu makan dulu,” ujarnya.
Aku
mengangguk pelan dan kembali ke kamarku. Tiba-tiba aku teringat bahwa ada
sesuatu yang belum kuberitahu pada kakakku. Kuputuskan untuk kembali menemui
kakakku namun langkahku terhenti saat kulihat pintu kamar kakakku terbuka
sedikit. Lewat celah kecil itu aku dapat melihat kakakku sedang duduk
membelakangi pintu, berbicara dengan seseorang di telpon. Saat namaku ia sebut,
aku tertarik untuk menguping pembicaraan mereka.
“Udah. Aku udah sampai rumah kok.
Tania juga kayaknya baru bangun barusan. Nggak, Dik. Dia nggak
tahu. Yang tahu cuman aku dan aku
sengaja nggak kasih tau dia. Tania marah-marah sepanjang
jalan dan akhirnya nangis. Pas kita
turun jembatan flyover, jalanan mulai
macet. Ya, macet depan kompleks pemakaman Pandu. Dari belakang ada yang kasih
klakson beberapa kali. Penasaran, aku lihat spion belakang. Taunya aku lihat ada orang di seat belakang. Apa? Astaga Tuhan, aku nggak bohong, Dika! Aku lihat ada
perempuan duduk di seat belakang dan
itu bukan pertama kali aku mengalami hal semacam itu! Tania masih nangis dan marah-marah. Kalau aku ngomong sama dia, pasti dia bakalan lihat ke aku dan dia bisa lihat seat belakang. Kamu ‘kan tahu sendiri
Tania takut banget sama hal kayak gitu. Akhirnya aku diam aja
sepanjang jalan sampai sosok perempuan itu hilang pas kita lewat depan Shell.
Dika, aku sendiri takut! Perempuan itu sekitar umur tiga puluh tahunan, pakai
gaun warna putih. Bukan itu yang aku takutin!
Masalahnya, mulut sama dua mata perempuan itu dijahit benang hitam!”
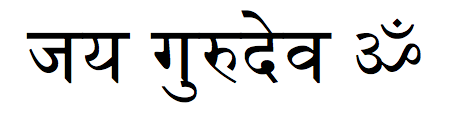





%2B1.png)

