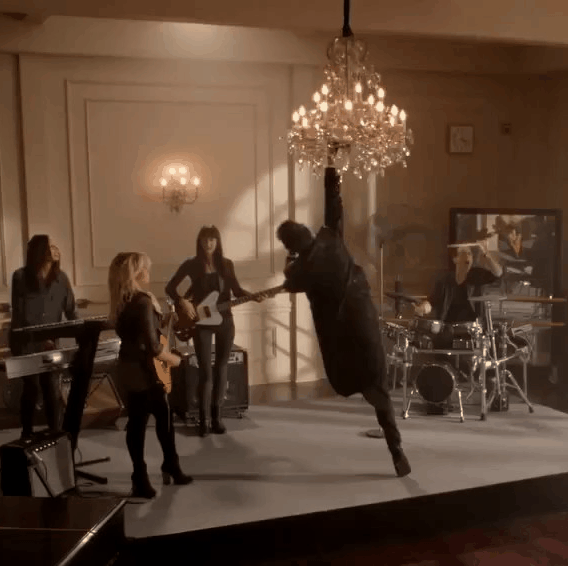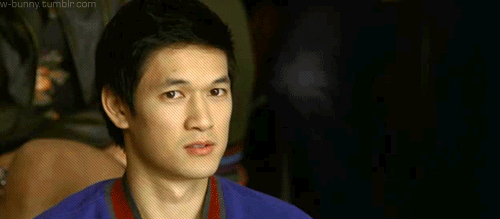Langkah-langkah itu terdengar semakin mengesalkan. Mas Eza terus berjalan, bolak-balik di depan pintu besar berwarna hijau itu. Di ruangan ini, hanya suara langkah kakinya yang mendominasi, membuat ritme dengan kecepatan tetap seperti ketukan bebas pada tempo moderato. Pria paruh baya yang duduk di bangku di pojok ruangan tak menghiraukan mas Eza yang sedang panik, nampak membaca koran dengan santainya. Seorang ibu dan anaknya yang duduk tak jauh dariku juga nampak mengacuhkan mas Eza yang sejak tadi entah sudah berapa kali mondar-mandir di hadapan mereka. Ibu dan anak itu sedang asyik mengobrol sembari menikmati kudapan kecil yang ada dalam lunch box berwarna biru muda.
“Mau, dek?” ibu tersebut tiba-tiba menawarkan sepotong kue gulung coklat padaku.
“Oh. Nggak apa-apa, bu. Saya udah makan,” jawabku.
“Eh nggak apa-apa! Ambil aja, dek. Anak saya nggak suka kue coklat soalnya,” ujar ibu itu setengah memaksa.
Aku mengangguk pelan dan ragu-ragu menerima kue pemberian ibu tersebut. Setelah berterima kasih, aku memutuskan untuk memakan kue coklat itu. Rasanya lezat dan krim coklat yang berada di antara layer kue terasa begitu manis. Sayang sekali kakakku terlalu panik saat ini sehingga tak menyadari bahwa kue yang lezat ini ada di tanganku.
“Anak pertama ya, dek?” tanya ibu itu lagi.
“Eh?” aku terkejut.
“Ya, ini si mas lagi nunggu kelahiran anak pertamanya ya?” jelas ibu itu.
“Oh. Ya, bu,” jawabku pelan.
“Pantesan panik begitu. Beda sama saya,” balasnya.
“Memang ibu nunggu siapa?”
“Adik saya.. melahirkan anak kelima”
“K-kelima?”
Aku terkejut mendengar ucapan ibu tersebut. Pantas saja ibu itu nampak tenang sementara kakakku saat ini keadaannya sedang uring-uringan. Kali ini mas Eza mencoba untuk duduk tenang, meskipun pada akhirnya tetap saja ia menggerutu, berbicara sendiri dan menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya dengan cepat. Ia tak bisa duduk tenang lebih dari dua menit dan akan kembali berdiri, berjalan mondar-mandir di depan pintu menuju ruang bersalin dan sesekali mencoba mengintip melalui jendela kecil yang ada di pintu tersebut yang, sayangnya, tertutupi oleh tirai berwarna biru tua.
“Kok lama banget sih!” gerutunya seraya mondar-mandir, kali ini, di hadapanku.
“Melahirkan ‘kan nggak bisa cepat begitu aja, mas,” jawabku.
“Ya, tapi ini bikin aku jadi was-was! Kalau terjadi apa-apa sama Alia, nanti gimana?” balasnya.
“Mbak Alia ‘kan nggak melahirkan sendiri. Dia dibantu sama bidan,” jawabku.
Mas Eza meringis kesal. Ia lalu menghentikan langkahnya dan mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan ketegangan dalam dirinya, namun tetap saja cara itu tak berhasil membuatnya merasa lebih tenang. Ia kembali duduk di sampingku dan tetap menggerutu sembari sesekali menepuk-nepuk telapak kakinya ke lantai. Peraduan sol sepatu dan ubin membuat suara yang, meskipun tak begitu berisik, membuatku merasa terganggu. Tak bisakah ia bersikap jauh lebih tenang? Aku tahu proses kelahiran merupakan proses yang menegangkan, tapi jika disikapi dengan cara seperti ini kurasa hanya akan menghabiskan energi saja.
“Mas Eza mau minum? Biar Rey belikan mi—“
“Udah kamu duduk disini!” bentak mas Eza.
Aku meringis pelan. Mas Eza kembali mondar-mandir di depan pintu ruang bersalin dan aku masih dapat mendengar gerutuannya. Monolog-monolog kecil seperti “Ya Allah, kapan beresnya ini?”, “Ya Allah, gimana ini?” atau “Aduh! Alia cepat beres dong!” terdengar cukup jelas olehku. Aku memperhatikan kembali sekelilingku. Para penunggu pasien nampak tak sepanik kakakku dan mereka nampak tenang, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing tanpa menunjukkan ekspresi panik atau gugup. Ada empat orang ibu yang melahirkan malam ini—satu diantaranya adalah kakak iparku, mbak Alia.
“Mas, melahirkan itu proses yang butuh waktu nggak sebentar,” tegasku seraya bangkit dari tempat dudukku dan menghampiri kakakku.
“Mas juga tahu, Rey! Makanya mas panik!” jawab kakakku tak sabar.
“Mas Eza panik seperti ini juga nggak akan bantu banyak dalam proses persalinan mbak Alia,” balasku.
“Kamu nggak lihat mas masih pakai kemeja kerja? Mas bahkan nggak sempat ganti baju!” ujarnya.
“Lha terus? Setidaknya mas pakai baju ke rumah sakit, ‘kan?” balasku.
“T-tapi ini.. Ah! Kamu nggak paham juga, Rey? Alia ada di dalam sana dan lagi melahirkan! Dia ada di antara hidup dan mati! Coba kamu bayangin situasi seperti itu dan posisikan diri kamu di posisi mas saat ini!”
“Rey tahu situasinya seperti apa, tapi kalau panik berlebihan seperti ini juga nggak baik”
Mas Eza menatapku tajam.
“Coba deh mas Eza lihat penunggu pasien yang lain. Mereka juga menghadapi situasi sama seperti yang mas Eza hadapi tapi mereka nggak panik kayak mas Eza,” jelasku.
“Terus kamu mau mas bisa tenang seperti mereka? Kamu nggak bisa minta semua orang buat punya pola pikir dan perasaan yang sama, Rey! Mereka lebih tenang mungkin karena mereka udah pernah mengalami hal ini sebelumnya, tapi mas baru pertama kali mengalami ini!” balasnya.
“Rey tahu, mas. Maksud Rey itu mas coba lebih tenang lagi. Jangan mondar-mandir dan menggerutu terus”
“Kalau kamu di posisi mas saat ini, emang kamu nggak akan panik seperti mas? Apa kamu bakalan santai sementara istri kamu lagi berjuang di dalam sana, antara hidup dan mati?!”
Aku menghela nafas sejenak.
“Aku nggak akan panik seperti mas,” jawabku tegas.
“Bohong kamu. Mas yakin kamu juga bakalan panik seperti mas sekarang,” sanggahnya.
“Rey nggak akan seperti itu. Panik berlebihan itu karena mas nggak siap secara mental. Harusnya sejak awal saat tahu bakalan jadi ayah, mas udah siap mental bahkan untuk di saat-saat seperti ini, tapi ternyata mas panik berlebihan. Mas nggak siap mental buat jadi ayah,” balasku.
Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku dan kali ini, semua orang yang ada di ruang tunggu melihatnya. Sial! Mengapa di saat aku ditampar, semua orang mengalihkan perhatiannya, namun tidak saat kakakku mondar-mandir di depan pintu? Aku harus menahan rasa sakit dan rasa malu secara bersamaan dan ini benar-benar bukan hal yang mudah bagiku. Kepalaku masih tertunduk namun aku bisa merasakan tatapan marah kakakku tertuju padaku. Kedua tanganku tiba-tiba gemetaran dan nafasku mulai kacau. Perlahan kuangkat wajahku dan kulihat wajah kakakku. Meneguk ludahnya sendiri, ia nampak pucat dan terkejut. Ia pasti terkejut oleh perbuatannya sendiri.
“Kamu harusnya nggak bicara seperti itu sama mas,” ujar mas Eza.
Aku segera pergi meninggalkan mas Eza, mengacuhkan tatapan orang-orang yang ada di ruang tunggu, berjalan entah kemana. Aku harus pergi dari tempat itu. Ya setidaknya sampai aku punya cukup keberanian untuk kembali lagi dan menahan malu. Pintu lift terbuka dan refleks aku segera melangkah masuk ke dalam lift dan menekan tombol menuju lantai dasar. Lift bergerak pelan dan kaki kananku menghentak lantai lift begitu saja, seolah-olah hentakkan kakiku dapat mempercepat laju kapsul lift. Pintu itu terbuka dan aku segera keluar dari lift, berjalan menuju lobi utama rumah sakit. Masih ada banyak orang disini, duduk sembari menonton televisi atau sibuk dengan ponselnya masing-masing. Aku segera mencari tempat duduk kosong lalu duduk, mengatur nafasku dan menyandarkan punggungku. Pipiku masih terasa perih setelah tamparan keras tadi. Sudut bibirku pun terasa perih. Ada titik darah saat kusentuh ujung bibirku dengan telunjukku.
“Brengsek!” umpatku pelan.
Aku menyeka darah di sudut bibirku dengan punggung tanganku. Kurasa luka di sudut bibirku tak begitu buruk dan kuharap luka itu cepat kering. Sekali lagi aku menghela nafas panjang lalu kupejamkan mataku. Apa aku salah? Kurasa aku salah. Ucapanku pasti sangat menyinggung perasaan kakakku. Aku seharusnya tak mengatakan hal itu dan memaklumi sikap kakakku yang saat ini sedang panik menunggu proses persalinan istrinya. Tapi mas Eza pun salah karena telah menamparkan di depan banyak orang. Ia telah membuatku sangat malu. Belum lagi pipiku terasa perih dan ada luka di sudut bibirku. Mengapa ia harus menamparku? Apa teguran atau bentakkan saja tak cukup? Dibentak di depan banyak orang pun sudah cukup membuatku malu.
“Kak, sudut bibirnya berdarah loh”
Aku membuka kedua mataku, menegakkan tubuhku dan menoleh ke sumber suara. Seorang anak laki-laki berusia sekitar sepuluh tahun duduk tak jauh dari sisi kiriku. Ia menunjuk ke arah sudut bibirku.
“Berdarah,” ujarnya.
“Oh”
Aku kembali menyeka sudut bibirku dengan punggung tanganku. Bocah itu meringis pelan.
“Pasti sakit,” ujarnya.
“Lumayan,” jawabku.
Bocah itu mengangguk pelan. Wajahnya nampak pucat dan sorot matanya begitu sayu. Anak ini pasti salah satu pasien di rumah sakit ini, tapi mengapa di malam hari seperti ini ia berkeliaran di luar kamarnya? Kemana orang tuanya?
“Dek, kok malah keluar kamar?” tanyaku.
“Bosan ah kak di kamar,” jawabnya polos, “Kalau disini ‘kan rame. Banyak orang”
“Nggak dicari mama papa emangnya?” tanyaku lagi.
“Mereka lagi tidur, kak,” jawabnya.
“Wah, nakal ya kamu. Kabur pas mama papa kamu tidur”
“Ya habisnya mau gimana lagi”
Aku tersenyum kecil. Sejak dulu aku memang tak pernah ingin untuk dirawat di rumah sakit, meskipun sakitku cukup parah. Aku sering menolak saat dokter merujukku untuk dirawat di rumah sakit dan sebisa mungkin berusaha agar dokter mengijinkanku menjalani perawatan di rumah. Penemuan tubuhku di dalam lemari pakaian setelah melakukan percobaan bunuh diri beberapa tahun yang lalu membuatku harus menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari dan hari-hari itu adalah saat-saat yang begitu membosankan. Aku harus memakan makanan yang serupa setiap harinya dan tak bisa banyak melakukan hal-hal yang kuinginkan. Tak ada biola. Tak ada gitar akustik. Aku benar-benar merasa sangat jenuh.
“Kamu sakit apa emangnya?” pertanyaan itu terlontar begitu saja.
“Kata papa aku kena demam berdarah,” jawabnya santai.
“Harusnya kamu istirahat. Jangan keluar kamar malam-malam begini,” balasku, “Kalau kondisi kamu memburuk gimana? Belum lagi nanti papa mama kamu bangun lalu lihat kamu tiba-tiba hilang, mereka nanti jadi panik”
Bocah itu hanya tersenyum kecil.
“Kakak lagi nunggu siapa disini?” tanyanya mengalihkan topik pembicaraan.
“Hmm.. Istrinya kakakku melahirkan,” jawabku.
“Harusnya kakak seneng, dong! Kenapa kakak keliatan lesu? ‘Kan nanti kakak bakalan punya keponakan. Bibir kakak juga berdarah,” tanyanya.
“Aku tadi sempat bertengkar sama kakakku,” jawabku, “Tapi nggak apa-apa kok. Kamu nggak perlu khawatir. Sekarang justru aku yang khawatir sama kamu”
“Kenapa harus khawatir sama aku? Kakak tenang aja. Kok kakak bisa bertengkar sama kakaknya kakak?”
“Kalaupun aku ceritakan kamu mungkin gak bakalan ngerti. Begitulah. Kakakku nggak tenang banget selama nunggu proses kelahiran istrinya, bolak-balik di depan pintu, duduknya nggak tenang dan menggerutu terus. Aku terus bilang ke kakakku kalau dia harus bersikap lebih tenang, tapi dia bilang kalau aku nggak paham situasi yang dia hadapi. Aku paham situasinya, makanya aku bisa suruh dia untuk tenang. Sikap dia yang kayak begitu justru menunjukkan kalau dia belum siap secara mental untuk jadi ayah. Setelah aku bilang gitu, aku ditampar keras di hadapan orang-orang banyak. Aku malu banget dan setelahnya aku langsung pergi”
Bocah itu menatapku bingung. Ah, sudah kuduga ia tak akan memahami keadaanku.
“Tuh, pasti kamu nggak paham. Aduh. Padahal sebetulnya aku cuma coba buat jujur aja supaya kakakku tahu kalau dia harusnya lebih mempersiapkan diri. Mungkin caraku salah, tapi aku emang harus jujur. Toh dia juga salah karena bikin aku malu di depan banyak orang. Ditampar itu sakitnya dua kali, sakit di pipi dan sakit hati. Dipermalukan depan umum begitu emangnya nggak mengesalkan?”
Aku menghela nafas pendek lalu menoleh ke arahnya.
“Kamu berapa tahun sih?” tanyaku.
“Sepuluh,” jawabnya.
Ah, tepat dugaanku. Ia berusia sepuluh tahun.
“Kayaknya kakak egois deh kalau kayak gitu,” ujarnya tiba-tiba.
“Eh?”
“Kalau menurut aku, kakak harusnya lebih memahami situasi yang kakaknya kakak hadapi. Nggak semua orang bisa seperti kakak, bisa bersikap lebih tenang dalam menghadapi sesuatu. Seandainya kakak ada di posisi dia, bisa jadi ‘kan kakak juga bakalan panik? Kakak nggak bisa paksa orang-orang untuk bisa bersikap seperti kakak, atau bisa satu pikiran sama kakak. Aku tahu perasaan kakaknya kakak saat ini. Istrinya lagi melahirkan dan kakaknya kakak pasti takut banget saat ini. Kakak ‘kan tahu melahirkan itu perjuangan antara hidup dan mati. Siapa sih yang mau kehilangan orang yang disayangi?”
“Ya sih.. Tapi—“
“Aku nggak berniat bikin kakak merasa bersalah tapi kalau menurut aku, bagusnya kakak emang nggak bicara seperti itu. Kata-kata kakak bikin kakaknya kakak tambah panik”
Aku menggigit bibir bawahku. Kurasa bocah ini benar. Ya, mungkin aku terlalu egois. Mungkin aku tak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Aku tak sepantasnya membuat kakakku semakin panik dengan ucapanku yang menyudutkannya, memandangnya belum siap untuk menjadi seorang ayah tanpa aku tahu ketakutan besar yang ia rasakan dan perjuangan yang telah ia lakukan sejauh ini. Saat ini mas Eza pasti sedang berada dalam ketakutan yang besar dan ia tahu ia tak bisa berbuat apapun untuk membantu mbak Alia dalam proses persalinannya kecuali berdoa. Berdoa, agar proses persalinan itu berjalan dengan lancar dan baik mbak Alia dan bayinya dapat selamat.
“Kakak kenapa? Kenapa diem aja?”
“Eh?”
“Maaf ya kak kalo kata-kata aku bikin kakak tersinggung”
“Oh. Nggak kok. Aku malah jadi tersadarkan sama kata-kata kamu. Makasih ya”
Bocah itu mengangguk pelan. Ia lalu bangun dari tempat duduknya, mengenakan sandalnya dan menaikkan zipper sweater biru tuanya.
“Aku harus pergi sekarang,” ujarnya.
“Kamu harus ke kamar sekarang. Nanti mama papamu cari loh,” jawabku.
“Ya. Kakak jangan sedih lagi, ya. Cepat baikan sama kakaknya,” balasnya.
Aku tersenyum kecil.
“Eh, sebentar!” tahanku.
“Ya?”
“Nama kamu siapa?”
“Niko, kak”
Bocah itu tersenyum, menampakkan deretan giginya yang putih. Aku membalas senyumnya. Ia kemudian berlari dan menghilang di ujung koridor. Aku meringis pelan. Kurasa memang ini salahku. Aku harus bertemu mas Eza. Kurasa perasaan malu itu memang layak kudapatkan. Aku pernah membuat mas Eza sakit hati sebelumnya dan aku tak ingin hal itu terjadi lagi. Aku harus segera meminta maaf padanya. Dan sebelum aku benar-benar bangun dari tempat dudukku, kulihat mas Eza muncul di ujung koridor, setengah berlari menghampiriku. Sosoknya yang tinggi kini berdiri di hadapanku. Ia terengah-engah, namun mencoba tersenyum, dengan mata yang berkaca-kaca dan bekas air mata di kedua pipinya.
“Perempuan,” ujarnya seraya tersenyum bahagia.
Seketika kakakku memelukku dan kudengar ia menangis. Aku menepuk punggungnya pelan. Dalam pelukannya aku juga mendengar kakakku mengucap syukur. Penantian yang melelahkan itu telah berakhir dan kini, kakakku secara resmi telah menjadi seorang ayah. Anak perempuan, dan itu artinya aku memiliki seorang keponakan perempuan yang, kuharap saat ia beranjak dewasa nanti, akan tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik seperti ibunya. Mas Eza melepaskan pelukannya. Ia lalu menyeka air matanya dan tersenyum lega.
“Mas sekarang jadi ayah, Rey,” ujarnya.
“Mas, Rey mau minta maaf buat—“
“Kamu harus lihat bayinya, Rey! Dia cantik”
“Tapi mas, tadi Rey udah bicara—“
“Mas nggak peduli, Rey. Mas senang banget saat ini”
Mas Eza lalu menarik lenganku dan membawaku menuju lift. Ia menekan tombol lift dan sambil menunggu, aku masih dapat mendengar ia mengucap syukur atas kelahiran anak pertamanya. Aku turut bahagia atas kelahiran anak pertama kakakku. Tanpa kakakku beritahu, aku yakin pasti bahwa bayi itu sangat cantik dan kelak akan tumbuh menjadi gadis yang cantik.
“Mas, Rey minta maaf buat yang tadi,” tegasku.
“Itu nggak jadi masalah, Rey. Mas juga minta maaf karena tadi sempat tampar kamu di depan banyak orang,” jawabnya.
“Rey pantas kok ditampar kayak gitu. Memang Rey yang salah. Rey minta maaf, mas,” balasku.
Mas Eza mengusap rambutku. Pintu lift terbuka dan keluarlah tiga orang perawat yang mendorong sebuah ranjang, dengan satu sosok yang sekujur tubuhnya tertutupi oleh kain berwarna biru muda. Menyusul di belakangnya, sepasang suami istri nampak sedang berduka. Sang suami merangkul erat istrinya yang menangis tersedu-sedu. Ranjang itu lewat tepat dihadapanku dan saat kain biru muda itu tersingkap, aku melihat sweater biru tua yang dikenakan sosok yang terbujur kaku itu. Aku tak dapat melihat wajahnya namun aku rasa tanpa perlu membuka kain itu, aku akan mengenal wajah yang ada dibaliknya.
“Kenapa harus sekarang, pa? Kenapa harus Niko?”
Tangisan sang istri terdengar jelas di telingaku dan seketika menusuk perasaanku. Mas Eza merangkul bahuku dengan erat. Kami masih terpaku di tempat, memandang pasangan yang berduka itu mengantar anaknya sampai akhirnya mereka hilang dari pandangan kami setelah berbelok ke sebuah koridor.
“Innalillahi,” ujar mas Eza.
Pintu lift mulai menutup dan dengan segera mas Eza menekan tombol lift untuk menahan pintunya. Ia masih merangkulku dan membawaku masuk ke dalam lift. Tombol lantai nomor delapan ditekannya dan pintu lift pun mulai menutup.
Perasaanku begitu kacau. Tenggorokanku terasa begitu panas dan air mata pun mengalir dari kedua mataku. Aku tak dapat mempercayai apa yang baru saja kulihat. Semuanya terjadi begitu cepat. Sesaat yang lalu bocah itu masih tersenyum bahagia, berbicara padaku dengan kepolosan seorang anak berusia sepuluh tahun. Sweater biru muda dan Crocs merah marun. Ia bahkan sempat memberiku saran yang membuatku sadar akan keegoisanku pada kakakku. Bocah sepuluh tahun itu datang dan pergi begitu saja, lalu kusadari bahwa aku tak akan pernah melihatnya lagi. Ini tak adil. Hidup memang tak adil. Mengapa harus anak itu? Mengapa harus Niko? Mengapa harus secepat ini, di saat kedua orangtuanya masih ingin bersamanya dan melihatnya tumbuh dewasa? Mengapa harus secepat ini, di saat aku baru mengenalnya dan aku tak sempat berterima kasih karena telah mengajarkanku sebuah pelajaran kecil yang begitu berharga? Dan ditengah-tengah perasaan yang menyayat itu, sebuah pertanyaan tentang anak itu terlintas di benakku. Apakah itu benar Niko, yang duduk di sampingku dan berbicara padaku? Semuanya terjadi benar-benar sangat cepat dan aku mulai meragukan siapakah ia sebenarnya, bocah kecil yang berbicara denganku beberapa saat yang lalu.
Dan tangisku pun akhirnya meledak. Suara tangisanku memecah keheningan di dalam lift. Mas Eza kembali memelukku dan mencoba menenangkanku. Ia mengusap rambutku dan menepuk bahuku, memintaku untuk tenang dan membuatku percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja.
“Udah, Rey. Mas nggak marah sama kamu. Kamu nggak perlu kayak gini. Mas benar-benar nggak marah kok. Percaya deh. Mas maafin Rey untuk kejadian yang tadi,” ujarnya.
Sayangnya, kakakku tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Ia tak tahu.